Aku Takut Kawin, Mak!
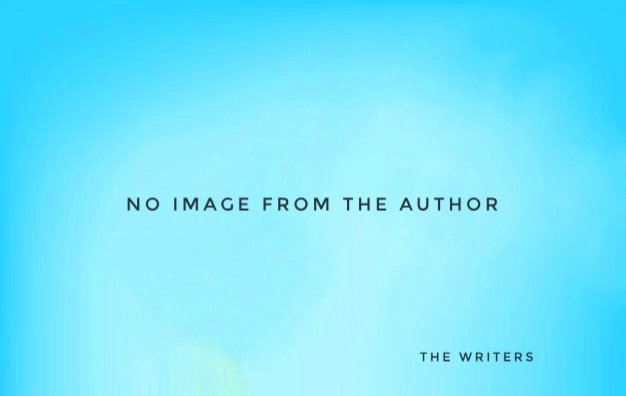
Usiaku saat itu sudah 30. Status, belum kawin! Eh, belum nikah.
Empat dari enam adikku sudah lebih dulu ke pelaminan. Gimana perasaan disalip oleh empat orang adik lebih dulu?
Marahkah? Irikah? Sakit hatikah?
Big no! Aku justru kagum. Mereka lebih berani mengambil keputusan hidup. Aku sendiri memang belum seberani itu. Setidaknya untuk saat itu.
Kepalaku masih penuh dengan kalkulasi. Sibuk dengan hitung-hitungan. Jika begini maka begitu, jika begitu maka begitulah.
Pertama ada masalah temperamen yang saat itu belum bisa kukuasai dengan baik. Khawatir, nanti jika ada selisih, bisa-bisa aku membahayakan istri.
Kedua, ada masalah egoisme, juga masih terlalu tebal. Tak bisa dibawa ke pernikahan yang notabene membutuhkan kemampuan mengalah.
Di sana butuh kejernihan membaca dan memecahkan persoalan, jika tidak bisa-bisa seumur-umur larut dalam persoalan itu-itu saja.
Selain itu, tentu saja soal gaji. Dengan gaji yang masih di bawah lima juta ketika itu, kupastikan tak mudah buat hidup di Jakarta.
***
Ada beberapa gadis mengajak nikah. Iya, diajak menikah (boleh sombong dikit, ya?).
Pekerjaan mereka saat itu lebih menjanjikan dibandingkan pekerjaanku. Aku memilih menggelengkan kepala.
Bahkan ada kerabat mencoba mendikteku. "Kau kawinlah dengan si pulanah. Pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, keturunan orang terpandang, masa depanmu menjanjikan..."
Kupilih membatu. Kudiamkan.
Kepala batuku sudah disesaki sederet kalimat. "Laki-laki macam apa yang kawin dan hidup di ketiak istri?"
Tidak kuluapkan. Kecuali sekadar membantah sekadarnya saja.
"Aku belum cukup yakin buat kawin. Soal lapar, aku sendiri sudah biasa hidup dengan lapar. Aku kuat menahan lapar. Tapi kurasa-rasa, aku takkan kuat jika melihat anak istriku kelak jika sampai kelaparan."
Kira-kira begitulah dalihku, dengan sedikit ekspresi melotot. Sebagai pesan tersirat, soal prinsip hidup, jangan coba-coba mendikteku.
Ya, ini memang tidak lepas dari pesan yang pernah kudapat dari seorang penulis Amerika Serikat, dan juga entertainer. Steve Harvey, namanya.
Kata dia dalam satu wawancara, "Terkadang, soal ke mana kau ingin membawa hidupmu, memang tidak perlu diceritakan kepada siapa-siapa. Mereka takkan bisa melihatnya, karena bisa jadi itu cuma diperlihatkan Tuhan hanya kepadamu."
Sederet kalimat ini lumayan membantu kepala batuku tetap sekeras batu. Batu yang takkan gampang dipalu.
Eh, itu empat orang adikku sudah lebih dulu ke penghulu? Tak kupusingkan.
Eh, adik-adikku satu demi satu sudah punya anak? Ini sih yang sempat bikin aku gundah.
"Gue kapan punya anak?" Itu yang pelan-pelan meluluhkan pertahananku. Dari cerita pernikahan, yang paling kuidamkan memang memiliki anak yang lucu-lucu.
Ditambah kalimat pendek dari calon istri, "Keluarga udah nanya kapan bla... bla... bla."
Intinya, kalo mau nikah, lamaran secepatnya, nikah secepatnya. Semacam ada pesan tersirat, jangan buang waktu cuma untuk proses pengenalan terlalu jauh.
"Laki-laki macam apa yang cuma mau punya pasangan tapi tak berani menikah?" Itu bukan kata calon istri. Itu kataku sendiri, untuk membantu kepalaku lebih lunak.
Yakin? Tidak.
Sudah berani? Belum.
Siap? Tidak.
Tapi, merasa aku sedang ditantang, kujawab tantangan itu dengan kepala tegak.
Diminta penuhi acara lamaran, kupenuhi. Diminta penuhi mahar, kupenuhi. Diminta tambahi biaya pesta pernikahan, kupenuhi.
Di belakang layar, ada dua teman ikut terlibat. Mereka meminjamkan sekian banyak, menutupi kekurangan tersisa yang tak terjangkau gajiku saat itu.
Jadilah akhirnya aku bisa ke penghulu. Di depan mata mendiang bapakku.
Beliau terbang dari Aceh ke Jakarta, lalu ke Bandung, melihat pernikahan anaknya. Saat usia beliau sudah terbilang senja.
Sejujurnya, uangku saat itu sangat terbatas. Saat beliau berterus terang sedang tak punya tabungan untuk tiket pesawat, tetap kupaksa datang.
Syukurnya, ada saja rezeki hingga bisa menghadirkan beliau ke pernikahan. Sekaligus, menjadi pengalaman pertama beliau menginjak tanah Jawa.
Sebelum itu, beliau hanya jatuh cinta pada tanah kelahirannya. Tak tergoda untuk melangkah ke tanah-tanah lain di negara ini. Kecuali ketika anaknya menikah.
"Bapak sudah terlalu tua untuk menginginkan yang muluk-muluk." Begitu kata beliau saat itu.
Sekaligus ada gerimis turun dari sisi matanya. Sebab aku menikah saat beliau sudah menua, dan tak lagi bisa memberi apa-apa.
"Ya, bapak sedih, kamu menikah tapi tidak bisa memberimu apa-apa."
"Pak... Buatku, seharusnya bapak tidak perlu bersedih. Sebab semua anak bapak yang laki-laki punya kesamaan cita-cita; menikah tanpa perlu membebani bapak. Ini bukti, bapak berhasil mendidik kami menjadi laki-laki."
Air mata mengucur deras di wajah beliau. Kupeluk beliau, seperti beliau memelukku saat kecil dulu setiap kali aku bersedih.
"Soal aku telat menikah, lah ini bukan salah bapak. Ini pilihanku sendiri. Sedikit telat, tapi masih sempat bapak lihat sendiri, kan?" Candaku, cuma demi bisa melihat tawanya yang lengkap dengan gusi tanpa gigi lagi.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.







































